Ambang Batas yang Getas, Suara Rakyat yang Diretas
Oleh: Mink Ismail
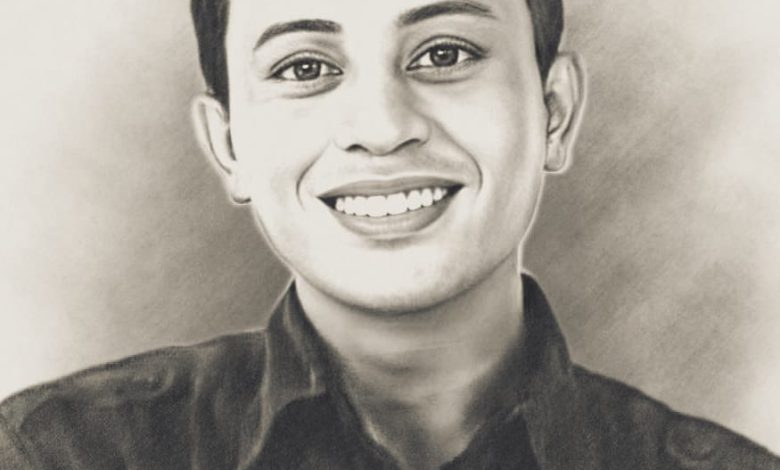
Abadikini.com – Ketika filsuf Prancis Jacques Derrida memaklumatkan demokrasi sebagai yang akan datang, to come. Ungkapan bernada aporistis ini rasanya sulit dipahami. Apa yang dimaksud Derrida dengan demokrasi akan datang? Mungkinkah ia (demokrasi) sebuah kemustahilan kini, dan hanya akan tiba di masa mendatang, tapi kapan? Atau memang demokrasi yang banyak dipikirkan itu sebatas angan atau ideal yang hanya ada dalam bayangan pikiran semata? Entahlah!
Dalam praktiknya demokrasi memang bukan cerminan demokrasi itu sendiri. Ada jurang antara yang kita pikirkan dengan yang sejatinya terjadi. Ada ketegangan epistemik juga praksis. Karena itu barangkali Karl Marx juga Angel tak percaya demokrasi. Demokrasi barangkali, seperti kicau burung yang indah didengar, tapi penuh tipu daya agar para taipan mudah mengeruk cuan.
Pluralisasi atau Polarisasi?
Dalam praktiknya demokrasi hanya memperluas distribusi kekuasaan elit. Kekuasaan politik juga telah menumpulkan kehendak baik manusia setelah kehendak umum (nature of state) ala Rosseau menyelinap dalam ruang privat.
Meski jalan poltik etis dimana ‘polis’ atau kota Athena cerminan demos dan kratos (kuasa rakyat) pernah dirintis Plato juga Aristoteles. Tapi bayangan ideal demokrasi itu teramat lacur setelah praktik ala filsafat Nicollo Machiavelly merajalela di republik ini.
Sentimen kawan dan lawan terus dipelihara. Umbar caci maki merebak di media sosial. Gagasan ditepikan karena pembelahan dukungan membabi buta.
Demi kekuasaan mereka tak peduli agama diobral untuk memanaskan lawan, ayat-ayat dicungkil demi kepentingan menyerang lawan, bahkan cuan ditebar demi mengobarkan api perang merebut kekuasaan.
Kodrat kehendak baik manusia telah diretas, bersamaan dengan begitu mudahnya elit menggiring, memanasi rakyat, bahkan menjerumuskannya ke kebodohan yang akut.
Ya, seperti kata Machiavelly dalam Ill Principle; rakyat tak ubahnya kerbau, ikutilah maunya, berilah makan yang cukup, maka kau akan mudah menggiringnya. Jadilah gembala yang baik karena kerbau mudah digiring kemana saja.
Contohnya saja kalau kita berkaca dari kaum pencerah, atau obrolan kaum cerdik pandai. Mereka selalu menggaungkan pentingnya demokrasi sebagai medan untuk merayakan semangat pluralisasi atau keragaman dalam kesadaran politik warga. Tapi pada kenyataannya sistem pemilu kita justru melahirkan aturan yang justru melahirkan praktik politik polarisasi yang amat rentan benturan.
Pembelahan massa sangat jelas kentara hingga melahirkan istilah atau sebutan pasukan ‘cebong’ versus ‘kampret’. Pembelahan ini bahkan awet dan dipelihara kedua kubu partai rival. Mereka sama-sama gemar memproduksi isu dan framing yang membelah, tak peduli jika itu harus menjual sentiman agama hingga ‘menjual’ ayat Tuhan.
“Ambang Batas yang getas”
Lahirnya polarisasi di tengah masyarakat sesungguhnya mulai disadari banyak kalangan, bahkan diinsyafi partai pendukung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dulu jumawa dengan kebijakan ambang batas, hingga mematok syarat presentasi besar 20 persen.
Mereka kala itu tak pernah membayangkan perolehan partainya akan merosot, seperti PAN dan Demokrat sendiri. Mereka lupa kalau sejarah adalah perjalanan takdir yang tak selalu bisa diterka.
Kalau idealnya demokrasi itu ibarat menu makanan dengan sajian beragam, lalu kenapa selera pemilih dibatasi dengan pilihan menu ambang batas 20 persen untuk memilih pemimpin. Yang terjadi akhirnya partai politik yang sejatinya jadi pilar yang mampu melahirkan pemimpin, justru terperangkap koalisi model arisan ala sosialita petinggi partai yang sarat transaksional.
Karena ambang batas, partai dibuat tak percaya diri menyodorkan pemimpin atau jagoannya yang sudah ditempa, sebab harus berkompromi untuk memenuhi jumlah ambang batas.
Bahkan ada banyak partai yang terpaksa menahan atau mengalah untuk menampilkan jagoannya di laga pilpres sebagai sajian rakyat, hanya karena harus bersepakat dengan teman satu arisan koalisinya.
Belum lagi kadang mereka rela membenamkan jagoannya demi cuan atau mahar politik yang menggiurkan dalam politik serba transaksional. Seperti gejala tarik ulur pada arisan partai Demokrat, Nasdem dan PKS hari-hari belakangan ini.
Di sisi lain, bagi partai yang cukup besar yang hanya perlu tambahan sedikit saja bisa seenaknya menentukan pilihan sesuai selera Ketua Umumnya tanpa perlu mendengar atau mempertimbangkan kriteria ideal pemimpin.
Megawati Soekarnoputri misalnya, tinggal bilang; “ya terserah gw gitu loh, kan sesuai mandat partai saya yang punya hak prerogatif menentukan siapa calon presiden, ” demikian katanya di sela sambutan di hadapan kader PDI Perjuangan belum lama ini.
Masalah lainnya, yang juga jadi pertanyaan dari aturan ambang batas presidential threshold yang kadung sudah disahkan Mahkamah Konstitusi itu juga terkait dengan anmosfir atau suasana pemilihan saat ini dengan segala dinamika dan perubahannya, justru diukur dengan tolak ukur perolehan suara di masa lalu. Bagaimana mungkin pilihan kita untuk menu hari ini, justru didikte syarat ‘belanjaan’ menu masa lalu yang mungkin sudah basi? Bukankah kontradiktif dengan demokrasi yang sejatinya bisa menjawab kekinian?
Masalah lain yang mendera bangsa kita adalah kepura-puraan dan ke-tidak-mantapan kita memegang universum ideal demokrasi yang sesungguhnya, karena itu sikap dekontruktif hilang dari khazanah demokrasi.
Contoh paling gamblang adalah ketika partai politik yang sejatinya jadi pilar demokrasi, sebagaimana disebut ilmuan politik Herbert Feith, justru kini perannya merosot sebagai institusi yang harusnya bisa melahirkan kader-kader terbaik.
Proporsional Terbuka ‘Arena Perjudian Terbuka’
Jika pun ada upaya ke arah itu, ketangguhannya dicederai sendiri oleh kebijakan sistem proporsional terbuka ketika kontestasi merebut suara dihelat.
Proporsional terbuka bukan hanya melemahkan kinerja partai untuk mempersiapkan kader, tapi juga membuat partai hanya sekadar juru stempel untuk mencalonkan kadernya pada pemilihan calon legislatif bahkan calon presiden.
Partai akan secara instan menjaring figur-figur populer dan berduit, soal kemampuan gagasan dan teknis menjadi anggota dewan, itu urusan belakangan.
Maka wajar setiap kali jelang Pemilu ketua-ketua partai rajin sowan mencari bibit-bibit unggulan figur di luar partai untuk mengeruk suara. Mulai keliling ke kelompok arisan artis, atau ke cukong-cukong berduit yang barangkali anak, menantu, keponakan atau isteinya bisa dicalonkan untuk laga pileg.
Dengan sistem proporsional terbuka, mental parpol pun jadi serba ‘tarkam’, cari jagoan darimana saja asal kuat bayar. Keterwakilan perempuan diabaikan. Kriteria ideal demokrasi makin dilacurkan ketika pertarungan partai tak hanya terjadi antar partai, tapi figur-figur di internal berjibaku perang sengit saling mengalahkan kawan dari dalam dengan kuasa modal dan jaringan.
Malahan, persaingan merebut kursi di internal lebih sengit ketimbang dengan rival partai lainnya.
Itu baru di level elit, di level bawah gelaran Pemilu bak gelaran saweran rakyat. Aturan main proporsional terbuka ini seolah menyuburkan semangat Pemilu ala pemilihan kepala desa paling bar-bar.
Serangan fajar berseliweran, medan perkumpulan konstituen harus bertabur cuan. Kalau caleg bawa program atau hanya datang bawa pikiran hanya akan dianggap sebagai janji di atas awan.
Atau nama kebebasan, disadari atau tidak, demokrasi kita bukan hanya telah dirampas oleh para oligarkis, tapi juga sudah tertawan oleh mental pembuat aturan perjudian.
Demokrasi atau suara rakyat benar-benar sudah diretas lewat aturan. Ambang batas itu sudah getas, tapi elit di atas justru tak kunjung bisa mengelupas luka demokrasi. Bagi sebagian elit pragmatia mungkin luka itu mudah diobati oleh obat mujarab yang dibeli dari hasil merampas uang rakyat.
Jadi benar kata Derrida, democracy to come, bukan kini atau kemarin, mungkin entah yang akan datang!
Oleh: Mink Ismail,
Esais Kebudayaan




